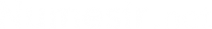Dimana pun kita duduk, baik di forum formal atau bukan, kita sebagai bagian dari masisir sering kali dihadapkan pada persoalan generasi dan angkatan. Tak jarang topik itu bahkan sudah dirasakan terlalu penuh sehingga termuntahkan sebatas basa-basi. Biasanya orang-orang menggambarkan generasi terkini sebagai citra kemunduran masisir, bahwa ia lemah sebagai sekumpulan manusia, impoten untuk bersaing dengan generasi terdahulu. Generasi baru selalu diceritakan sebagai yang serba kalah dalam segala hal sementara, generasi terdahulu yang menjadi pemenang pada zamannya, menyalahkan dan membenarkan, di sisi lain menaruh harapan agar generasi baru menjadi seperti mereka.
Problem generasi ini sering kali dirujuk kepada pandangan kesenjangan generasi atau Generational Gap yang merefleksikan perbedaan mencolok satu generasi dari generasi sebelumnya dalam budaya, pandangan hidup dan moralitas. Pandangan ini membatasi generasi berdasarkan rentang waktu 25-30 tahun, bersesuaian dengan umur rata-rata manusia ketika memiliki anak pertama (lihat, Mitos Kesenjangan Generasi: Sebuah Teori Bias Kelas). Pandangan ini kemudian terciutkan dan tereduksi saat memasuki dunia masisir–khususnya intelektual (karena kita kebanyakan adalah mahasiswa)—berdasarkan rentang waktu 6-10 tahun, bersesuaian dengan rata-rata arus keluar-masuk masisir di sini.
Baik di Mesir maupun Indonesia tak jarang kita dapati berbagai label generasi, seperti Generasi Z, Generasi Millenial, Generasi 5.0, Generasi Muslim Millenial (?), yang keberadaan dan kesenjangannya sering diamplifikasi oleh media massa sebagai kenyataan objektif melalui sains. Namun, kita tak perlu bingung atau heboh, karena label-label ini berdasarkan penelitian pembanding tidak terlalu signifikan. Label generasional bukan lah prediktor kuat terhadap karakter individu. Menurut Cort W. Rudolf (lihat, Generations and Generational Differences) teori kesenjangan generasi adalah teori yang tak memiliki ruang untuk difalsifikasi, dan teori yang tak dapat difalsifikasi, dalam paradigma Popperian, bukanlah teori yang dapat dianggap ilmiah.
Problem kesenjangan generasi atau Generational Gap dapat dirunut sejak para fungsioanlis-strukturalis meramaikan problem generasi dalam teori-teori sosiologinya pada tahun 40-an. Termasuk di dalamnya adalah Karl Mannheim dan Ortega y Gasset. Alih-alih memandang generasi sebagai kenyataan geneaologis manusia dan persoalan familial, fungsionalis-strukturalis melihatnya sebagai bentukan sosial yang memiliki nilai, sikap dan kebiasaan yang berbeda dari generasi sebelumnya didasarkan pada sistem sosial dan perubahannya.
Namun Mannheim, berbeda dari fungsionalis-strukturalis yang lain, tidak menganggap generasi sebagai sekedar bentuk sosial yang diromantisasi yangterkesan mekanistik dan determinan atas sistem dan perubahan sosial sehingga mengesampingkan faktor biologis dan umur hanya sebagai unsur naratif. Mannheim tetap mengakui faktor biologis dan umur sebagai faktor signifikan dalam membentuk generasi sebagai unit; terutama dalam pembentukan pengalaman sosial (atau pengetahuan) berdasarkan garis waktu (nature of time). Koherensi antara yang sains dan yang sosial dalam sosiologi Mannheim seringkali menjadi alasan peneliti-peneliti problem generasi untuk merujuknya.
Mannheim berpijak pada premis bahwa setiap kelas sosial, termasuk generasi, ditentukan oleh posisi seseorang dalam lokasi sosialnya. Generasi, sebagai sebuah kelas, kesadarannya ditentukan oleh lokasi sosial berupa ruang sosial dan kenyataan historis yang mengelilinginya. Keterbatasannya dalam lingkup generasi, mempersempit lokasi sosial menjadi lokasi generasional yang menentukan pengetahuan seseorang di dalamnya terbatas pada pengalaman historis yang serupa dengan orang lain dalam satu generasinya. Seorang pemuda serupa pengalaman yang dia hayati dengan pengalaman pemuda yang lain. Pengalaman itu berbeda dari yang tua, yang seringkali merasa kebingungan ketika krisis terjadi karena respon-respon yang mereka hayati pada jamannya agaknya tak relevan dengan perubahan itu sendiri.
Kelas sosial dengan pengalaman historis yang sama ini diistilahkan oleh Mannheim dengan generasi aktual yang terbagi lagi menjadi unit-unit generasional, berdasarkan kesamaan perspektif dalam mengalami kenyataan historis. Generasi-generasi sebagai unit-unit kelas dibentuk berdasarkan perspektif pengalaman dan kegelisahan yang sama.
Jika kita tarik kembali kepada pembicaraan yang mengemuka di antara kita, masisir, kemunduran generasi baru dari generasi terdahulu tampak masuk akal (common sense), lebih-lebih jika disodorkan stigma-stigma yang sering diperbandingkan dalam pembicaraan itu. Dominasi generasi terdahulu seolah menjadi hantu yang cepat atau lambat menentukan stereotip atas generasi yang baru.
Kita seringkali masuk ke dalam persoalan kesenjangan generasi dan membuatnya sebagai topik pembicaraan di setiap waktu kita bertemu kawan, dengan membingkai generasi baru tak sementereng dari generasi terdahulu seolah karena semata-mata kesalahan generasi itu sendiri, melekatkannya dengan stigma sebagai yang dididik kurang oleh ponpesnya, yang terlalu sembrono mempertaruhkan kapasitas intelektualnya yang hanya sedang-sedang untuk berangkat ke negara ini, yang lahir di era tiktok.
Padahal apa yang sering diutarakan dengan “generasi baru” tak diragukan memiliki pengalaman khas atas perubahan sosial mereka, lokasi sosial yang mereka hayati berbeda dari generasi terdahulu. Mereka terbentuk dan membentuk ruang kesejarahan mereka dengan respon atas kekhasan jaman yang mereka tinggali.
Kita terlalu banyak menimbun pembicaraan atas “generasi baru” dari persoalannya sebagai generasi—umur atau arus masuk mahasiswa baru di negara ini—sehingga mengabaikan persoalan yang sebenarnya terjadi dalam dunia masisir. Alih-alih mempersoalkan faktor nyata kemunduran intelektual dan ketimpangan sosial di masisir, justru menganggap persoalannya adalah generasi. Kita sibuk melekatkan generasi baru dengan stigma-stigma yang hanya tampak masuk akal (common sense), alih-alih menalar benar tidaknya stigma itu pada dirinya sendiri (ponpes yang kurang mendidik, benarkah?)
Sementara itu setiap upaya untuk keluar dari persoalan kemunduran seringkali tak berjalan mulus, bahkan menjadi petaka baru. Ketika kritik diutarakan untuk otoritas tertentu (yang mengatur keran masuk mahasiswa baru ke sini) misalnya, dianggap tak elok untuk diutarakan. Atau, ketika kita berbicara tentang pesantren dan titik-titik kelemahannya, dianggap anti-pesantren dan seterusnya.