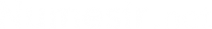Dalam sebuah pertemuan, saya pernah mendengar seseorang menceletuk bahwa Taha Husain adalah pemikir Islam transformatif. Karena itu sekadar celetukan, maka saya hanya bisa tersenyum dan menduga-duga bahwa penutur tidak begitu serius menyebutkan itu. Celetukan itu tertinggal di kepala saya sebagai lawakan dan akan saya bagikan kepada orang-orang yang akrab dengan Husain. Namun setelah saya pikir-pikir kembali, jika saja itu benar apa yang diyakini penutur dan celetukan itu lolos mulut di dalam forum terpelajar, maka itu bisa menjadi persoalan serius.
Taha Husain memang seorang pemikir dan kritikus sastra. Sebutan ‘pemikir Islam transformatif’ ini cukup menggelikan, sebab Husain tidak pernah membincang Islam sebagai topik utama dalam karya-karyanya. Sementara itu, frasa Islam transformatif ini hanya saya temukan dalam konteks keislaman Indonesia. Ulama Indonesia menyebut Islam transformatif, yang saya pahami sebagai Islam yang senantiasa ‘baru’ dan akomodatif dengan kehidupan nyata, mengadopsi istilah dan basis transformasi sosial; keniscayaan sejarah dan segala kebutuhannya. Seperti saya bilang, celetukan itu awalnya tinggal di kepala saya sebagai lawakan. Bisa dibayangkan jika Taha Husain didudukkan sejajar dengan Nurcholis Madjid atau Gus Dur.
Jika saja penutur meyakini Taha Husain sebagai pemikir Islam transformatif, maka ia belum memahami bagaimana sebuah perubahan pada waktu itu terjadi; bagaimana tradisi berbenturan dengan modernitas. Saya bahkan meragukan penutur memahami dan menilai sebuah tradisi yang dia anut. Bisa jadi, dia tidak menyadari bahwa dia hidup di era modern—bahkan pasca-modern?
Modernitas memang kental dengan pembaharuan. Topik semacam ini sering kali diangkat di lingkup Masisir. Di banyak forum, beragam kata digunakan untuk merayakan modernitas; tajdid, taghyir, tahawwul, hadatsah, muashirah dan istilah-istilah serapan bahasa Inggris seperti modernisasi, revitalisasi, rekonfigurasi, reformasi, transformasi, kontemporer dan lain-lain. Kata-kata itu berhamburan sampai saya tidak bernafsu hendak memilih yang mana, karena entah kenapa orang-orang menggunakan kata-kata itu dalam arti yang sama.
Namun, menarik jika modernitas ini kita ilustrasikan melalui kehadiran Taha Husain, lebih-lebih dalam karya Fî al-Syi’r al-Jâhiliy (1926), dimana dia meninjau kembali syair jahili yang sudah berabad-abad menjadi tradisi kuat dalam keilmuan Islam. Modernitas yang dialami Husain terjadi tanpa harus menghamburkan kata-kata itu, tidak terjebak dalam kerumitan kata-kata, hampir saya bilang spontan. Dia menyatakan dengan tulus bahwa dia mencintai berpikir dan melakukan riset, bersenang hati untuk membagikan hasil pikir dan risetnya kepada orang lain. Dia tidak peduli bahwa dia diterima atau dibenci karena menyampaikan hal-hal yang mereka sukai atau mereka hindari.
Husain memulai riset tersebut dengan memperlihatkan pertentangan di dalam wacana syair jahili. Dalam tradisi Islam, para perawi hampir bersepakat bahwa Arab terbagi menjadi dua; Qahtan yang menempati Yaman dan Adnan yang menempati Hijaz. Mereka bersepakat bahwa Qahtan adalah Arab yang semula dianugerahi bahasa Arab, disebut Arab Aribah. Sementara Adnan adalah keturunan Ismail bin Ibrahim yang mempelajari Arab Aribah dan menggeser bahasa yang sebelumnya mereka gunakan, Ibrani dan Aramea. Yang terakhir adalah Arab Musta’riba. Genealogi bahasa ini kemudian menjadi acuan berpikir kemudian, khususnya dalam sejarah dan filologi.
Para perawi, kata Husain, juga bersepakat pada perbedaan yang kuat antara bahasa Himyar, atau Yaman, dan Adnan berdasarkan riwayat dari Abu Amr bin Ala. Atas perbedaan ini Husain meragukan, bagaimana mungkin bahasa keturunan Ismail yang mempelajari Arab Aribah bisa jauh berbeda dari bahasa yang mereka pelajari sampai-sampai Ibnu Ala mengatakan kedua bahasa ini sangat berbeda. Dari keraguan ini, dia menampik kebenaran keberadaan Ismail dan Ibrahim; sekalipun al-Quran dan Taurat menyebutkan kedua nama tersebut, namun itu belum cukup untuk membenarkan keberadaan mereka secara historis; hanya dengan afirmasi kisah hijrah Ismail bin Ibrahim ke Makkah dan perkembangan Arab Musta’riba di kota itu.
Husain kemudian membincang keabsahan syair-syair jahili dalam lokus sejarah dan sastra. Dia menguji ragam dialek yang digunakan pada era jahiliah dan berujung pada prasangka bahwa masing-masing kabilah memiliki bahasa daerah yang diucapkan, kadang dituliskan, dan diekspresikan dengan beragam. Dia mengambil syair-syair hanya dalam kategori masyhur dan hanya dimiliki oleh beberapa kabilah.
Dalam pandangannya, seorang peneliti harus mampu menemukan perbedaan gaya penulisan di antara penyair-penyair itu dengan terang untuk sampai kepada keabsahan. Kendati Imruul Qays dari Kinda (Qahtan), Zuhair, Antarah dan Labid dari Qays, dan Tharafah, Amr bin Kalthum dan al-Harits bin Hillizah dari Rabiah, namun tidak ada keragaman dalam struktur dan pola rima di dalam syair-syair mereka. Semua syair tersebut disusun dan dituliskan dengan bentuk yang sama oleh penyair Muslim. Hal ini mengimplikasikan dua kemungkinan; mempercayai ketakragaman bahasa dan dialek di antara wilayah Arab; atau mengakui bahwa kebanyakan syair jahili disusun setelah Islam hadir. Husain memilih yang terakhir berdasarkan argumen bahwa tidak ada bahasa Arab yang tunggal di masa pra-Islam.
Penunggalan bahasa Arab hanya terjadi setelah penyebaran Islam dan mushaf al-Quran. Penunggalan tersebut terjadi karena al-Quran tidak terbaca dengan tepat oleh lidah non-Quraisy, sehingga kodifikasi dan pemberlakuan bahasa Arab Quraisy sebagai bahasa tunggal dilakukan. Dengan demikian, penunggalan ini, bagi Husain, sekaligus menawarkan kepada umat Muslim pada waktu itu bahasa pengantar (lingua franca) yang secara berangsur-angsur menggantikan dialek-dialek arab yang lain. Oleh karena ini, dia berpendapat bahwa syair-syair yang ada di tangan kita ini, tidak diragukan lagi, disusun dan ditulis pada era Islam.
Atas dasar kesimpulan itu Husain berargumen bahwa Arab mengumpulkan syair-syair jahili layaknya di dalam tradisi Yunani dan Romawi, untuk menyatakan supremasi atas tanah yang mereka tinggali. Itu tampak jelas ketika mengamati gerakan syair yang berkembang di era Umayyah yang hendak membangun asabiyah mereka di atas permukaan yang solid, memanfaatkan syair-syair jahili yang mengglorifikasi masa lalu. Karena syair yang asli masih belum ditemukan pada waktu itu, Husain percaya, penyair Umayyah menghadirkan syair-syair karangan mereka sendiri kemudian mereka tempelkan nama-nama penyair pada syair itu.
Dari keragu-raguan di atas, Husain berlanjut dengan menaruh kecurigaan kepada keaslian al-Quran. Dia menolak pendapat umum yang menyatakan bahwa Arab memiliki kekuasaan atas tanah Arab karena Tuhan telah mengirim nabi-nabi ‘muslim’nya berabad-abad sebelum Nabi Muhammad. Namun di dalam bukunya, keaslian al-Quran bukanlah pembahasan utama. Yang dia curigai adalah jika di dalam syair jahili terkandung motif Islam di dalamnya maka bukan tidak mungkin di dalam al-Quran terkandung karakter jahili di dalamnya.
Dengan buku Fî al-Syi’r al-Jâhiliy, Taha Husain menabrak tradisi. Mempertanyakan keberadaan al-Quran secara historis dan menampik kebenaran kisah Ismail dan Ibrahim di dalamnya, mengundang perhatian dan amarah ulama al-Azhar. Husain digiring ke pengadilan, didakwa murtad dan berakhir kepada larangan untuk mengedarkan bukunya. Husain diminta berbicara di depan umum dan menyatakan bahwa dia adalah Muslim yang baik. Rasyid Ridla dalam majalah al-Manar menuduh Husain “mencemari agama Islam dengan menampik apa yang dinyatakan di dalam al-Quran tentang Ibrahim dan Ismail.” Buku itu kemudian dicetak kembali dengan judul yang berbeda, Fî al-Adab al-Jâhiliy, dengan beberapa modifikasi di dalamnya, termasuk struktur buku.
Saya bukannya ingin membela Husain, namun saya salut dengan tindakannya. Keberanian itulah yang saya sebut bagian dari modernitas. Dia menyebutkan dalam bukunya sejak awal bahwa metode yang dia gunakan adalah skeptisisme ala Descartes—sangat modern bukan? Sekalipun saya menganggap itu hanya sebagai alibi, karena tidak ada ‘Descartes’ sama sekali dalam buku itu. Yang dilakukan Taha Husain dalam buku itu hanya menganalisis sastra Arab dan sejarahnya lepas dari pandangan ulama pada waktu itu atas tradisi yang mereka anut; afirmasi penuh atas syair-syair jahili, pendapat-pendapat atasnya oleh pembawa khabar, juru kisah, muhadits, mufasir dan penyusun historiografi Arab-Islam.
Yang Husain inginkan adalah “peneliti harus dilucuti dari pengetahuan yang telah lalu, menerima subjek penelitian kosong dari ide-ide yang mengelilinginya” dengan “melupakan sentimen kebangsaan dan seluruh kepribadiannya, melupakan sentimen religius dan segala yang berhubungan dengannya, melupakan apa yang menentang kedua sentimen ini.” Berangkat dari keraguan tentang kedua ikatan di atas, Husain bisa mengetahui sastra Arab dan sejarahnya dengan, “kami tidak berpegang pada apa pun dan kami tidak tunduk pada apa pun kecuali metode penelitian ilmiah yang benar.”
Saya kagum dengan keberanian Husain. Alih-alih menyumbang pemikiran baru dalam selubung tradisi dengan menginterpretasikannya sebagai produk tradisi, seperti yang dilakukan lazimnya ulama pada waktu itu, dia melakukan riset dengan mencabut syair jahili dari akar ‘kelahirannya’. Usaha itu tepat pada waktunya, ketika tradisi terpojokkan oleh modernitas di sekelilingnya dan perubahan-perubahan dirasakan sudah tidak terkendali.
Husain mendapat tuduhan dari tak hanya ulama Azhar, namun juga kalangan modernis. Abbas al-Aqqad keberatan dengan ‘ala Descartes’-nya Husain, sekalipun dia mengasumsikan bahwa Husain menggunakan metode itu. Serangan lain datang dari murid Husain sendiri di Universitas Kairo, Mahmud Syakir. Syakir mengatakan, dalam bukunya al-Mutanabbî bahwa tindakan Husain adalah plagiarisme karena pemalsuan syair jahili sudah lebih dulu ditulis oleh Margoliouth, seorang profesor bahasa Arab di Oxford, dalam jurnal berjudul The Origins of Arabic Poetry (1925). Rekan Syakir bernama al-Khudairi menerbitkan terjemahan jurnal Margoliouth dan menerjemahkan buku Discourse on Method untuk menjelaskan ide-ide Descartes.
Alih-alih roboh, Husain justru berdiri dengan kokoh. Fî al-Syi’r al-Jâhiliy masih tetap dipertimbangkan sebagai argumen yang cukup kuat dalam menguji keaslian syair jahili. Memang, dalam bukunya, Husain terlalu sembrono menggeneralisir syair jahili. Itu bagian yang tidak saya suka dari buku itu, semua dipukul rata sebagai tak asli. Namun kabar baiknya, penulisan sejarah Islam berikutnya, yang didasarkan atas syair jahili, mengambil sikap hati-hati dalam memilah sumber-sumber itu, seperti yang dilakukan oleh Jawad Ali dalam sepuluh jilidnya.
Dalam kehebohannya, Husain justru semakin mentereng. Saya setuju dengan anekdot al-Mazini tentang Husain dalam Tâhâ Husayn fî Mîzân al-Tasykîk; jika Husain adalah alumnus al-Azhar, bagaimana mungkin dia menulis tentang syair, bahkan ortografi arab? Lebih jauh lagi, Taha Husain adalah penyandang tunanetra, kenapa seorang buta tertarik dengan bagaimana kata-kata dieja? Di tahun 2300 M, saya bayangkan, mungkin saja para sejarawan mengira Taha Husain adalah nama pena yang disandang oleh beberapa penulis, layaknya kita meraba-raba tentang kesejarahan Homer dan Socrates.
Bagaimana dengan Taha Husain sebagai ‘pemikir Islam transformatif’?
Editor: Hamidatul Hasanah
Ilustrator: Khairuman