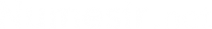Telah menjadi kemakluman bersama bahwasanya al-Quran sebagai kitab petunjuk dan hidayah (hudan lil muttaqin) memiliki kedudukan istimewa dalam hati setiap kaum muslim. Telah sejak fajar sejarah kaum muslim berbondong-bondong untuk memahami setiap detil dari kalam- kalam Tuhan tersebut. Di dalam kajian ilmu al-Quran, secara umum ayat-ayat di dalam kitab Allah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, al-muhkamat yaitu ayat-ayat yang jelas dari segi maknanya sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Kedua, al-mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang terdapat kesamaran dalam memahami maksud yang dikehendaki.
Para ulama kemudian bersilang pendapat dalam menyikapi jenis ayat yang kedua dalam dua mazhab. Kaum salaf/pendahulu memilih untuk mengembalikan sepenuhnya maksud dan makna dari ayat kepada Sang Mahatahu (al-tafwidh). Sedangkan kaum khalaf/para ulama yang datang setelah kurun-kurun awal memilih untuk memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang sesuai dengan keagungan Dzat Allah (al-takwil).
Golongan pertama berhati-hati dalam berurusan dengan kalam Allah sehingga memilih sikap “diam” dan “iman”. Sedangkan golongan kedua, melihat bahwa perintah Allah untuk memahami dan mendalami al-Quran harus dimaknai untuk mengupayakan pengetahuan pada setiap ayat dalam al-Quran, termasuk di dalamya ayat-ayat mutasyabihat. Tentu penakwilan tersebut tidak lepas dari kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan disepakati para ulama. Dua konsep ini terus diwariskan dari zaman ke zaman, sehingga telah masyhur bahwa keduanya adalah cara pandang golongan Suni (Ahlussunah wal Jamaah) dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat.
Kemudian pada abad ke-13 H datang seorang ulama bernama Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani dari Turki, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah. Ia mencoba mengkritisi kembali tradisi yang telah mapan tersebut. Ia menolak konsep takwil kaum khalaf, kemudian mengajukan ‘wajah baru’ dalam memaknai konsep tafwidl milik kaum salaf, khususnya dalam ayat-ayat mutasyabihat yang mengindikasikan keserupaan Allah dengan makhluk. Meski tidak dapat dipungkiri adanya keterpengaruhan Ibnu Taimiyyah dengan beberapa tokoh yang telah hidup pada kurun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa konsep yang dimaksud datang dengan argumen dan wajah yang baru.
Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa mazhab salaf dalam pemaknaan ayat-ayat mutasyabihat adalah membiarkan lafadz ‘sebagaimana adanya’, yaitu memaknianya dengan maknanya yang ‘hakiki’, sesuai dengan apa yang layak untuk disifatkan pada Allah. Ia berkata:
“Mazhab kaum salaf adalah menetapkan bagi Allah setiap sifat yang telah Ia nisbahkan pada diri-Nya serta yang telah dinisbahkan Rasulullah bagi-Nya. Kemudian menegasikan setiap sifat yang telah dinafikan oleh Allah atas diri-Nya, atau telah Rasulullah nafikan atas-Nya tanpa ada penyerupaan (dengan makhluk), penyelewengan makna… Dan mereka (kaum salaf) membiarkan ayat-ayat mutasyabihat ‘sebagaimana adanya’, karena yang ‘apa adanya’ bagi Allah tidaklah seperti yang tergambar pada hamba-Nya.”
Sebagai contoh, di dalam surat al-Fath ayat 10 Allah berfirman :”Tangan Allah di atas tangan mereka… “. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah disifati dengan tangan (al-yad) dengan maknanya yang hakiki, sesuai dengan yang layak dinisbatkan kepada-Nya.
Ia bersikukuh bahwa cara pemaknaan ini tidak mengandung unsur penyerupaan Allah dengan makhluk. Sebab menurutnya, “tangan” yang dinisbatkan kepada Allah berbeda dengan apa yang dapat digambarkan dan dimiliki oleh makhluk-Nya. Hanya Allah yang tau kaifiyyah atau hakikat dari “tangan” yang Ia nisbahkan pada diri-Nya tersebut.
Konsep ini jelas berbeda dengan makna tafwidl yang kita kenal, yaitu menyerahkan seutuhnya makna dan maksud dari ayat pada Sang Mahatahu. Ibnu Taimiyah dengan jelas mengatakan bahwa Ia disifati dengan “tangan” secara hakiki, baru setelah memberikan makna pada kalimat tangan (al-yad), ia menyerahkan (fawwadla-tafwidl) hakikat (kaifiyyah) “tangan” tersebut pada Allah. Begitu juga pada ayat yang menjelaskan bahwa Allah ber-istiwa’ di atas Arsy dan ayat-ayat semisalnya.
Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra, bahwa mazhab Ibnu Taimiyah dalam berurusan dengan ayat-ayat mutasyabihat yang mengindikasikan keserupaan Allah dengan makhluk kembali kepada dua poin utama. Pertama, menetapkan setiap yang tertulis di dalam al-Quran dan Hadits sahih. Sekiranya tidak ada penakwilan dan majaz pada lafaz-lafaz tersebut, sehingga lafaz tidak dikeluarkan dari makna hakikinya.
Kedua, meyakini bahwasanya zahir teks al-Quran dan Hadits tidak mengarahkan pada tasybih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Lantaran setiap hal yang Ia sebutkan dalam keduanya tidaklah serupa dengan apa yang dimilki oleh makhluk. Sebagaimana kita mengimani sifat pengetahuan (al-ilmu), kuasa (al-qudrah), kehendak (al-iradah), mendengar (al-sam’) dan melihat (al-bashar) tanpa bertanya bagaimana bentuk dan wujuk sifat-sifat tersebut dalam diri Allah, maka begitulah sifat tangan (al-yad), bersemayam (al-istiwa’) dan lain sebagainya seharusnya kita imani adanya bagi Allah.
Mungkin secara sekilas beberapa dari kita akan mengiyakan pemikiran Ibnu Taimiyah di atas, bahkan membenarkan. Toh, ‘tangan’ dan ‘wajah’ yang kita nisbatkan pada Allah berbeda dengan apa yang dapat digambarkan dan dimiliki makhluk. Padahal, jika kita cermati lebih dalam, kita dapat menemukan berbagai kerancuan di dalamnya. Pertama, terdapat kesalahan dari segi lafaz dan makna. Golongan salaf memaknai ayat-ayat mutasyabihat dengan maknanya yang hakiki, sesuai dengan yang layak dinisbatkan kepada Allah.
Dari segi lafaz, tidak ditemukan satu pun dari golongan salaf yang mengatakan ‘dengan maknanya yang hakiki’ dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi yang dapat diambil dari semisal perkataan Imam Malik :”al-istiwa telah diketahui. ‘Bagaimana’ tidaklah dapat dicapai akal. Pertanyaan tentangnya adalah bidah dan mengimaninya adalah kewajiban. Aku telah mengira bahwasanya engkau (orang yang bertanya) telah tersesat.”, adalah sikap tawaqquf; diam dan mengimani tanpa memberikan makna sama sekali pada ayat serta menyerahkan sepenuhnya makna dan maksud ayat pada Sang Mahatahu.
Diriwayatkan dari Imam Ahmad ketika ditanya perihal mustayabihat, ia berkata :”Kita beriman dan membenarkan (ayat-ayat tersebut) dan tanpa mencari hakikat dan makna (dalam ayat-ayat tersebut).” Bukankah Ibnu Taimiyah dalam hal ini telah menambah-nambahi apa yang tidak diucapkan oleh golongan salaf?
Dari segi makna, kalimat “memaknai dengan maknanya yang hakiki” mengindikasikan tindakan antromorfis (tasybih; penyerupaan Tuhan dengan makhluk). Namun, dalam kalimat “sesuai dengan yang layak dinisbatkan pada Allah” mengindikasikan bahwa ayat-ayat tersebut dimaknai bukan dengan makna hakiki, sebab tentu setiap hal yang mengarahkan pada penyerupaan tidak layak bagi-Nya. Ada kontradiksi di dalam kalimat yang ia utarakan.
Kedua, ia mengatakan bahwa kalimat tangan (al-yad), bersemayam (al-istiwa), wajah (al-wajhu) secara zahir tidak mengarah pada tindakan antromorfis. Padahal, sebagaimana dikatakan para ulama, lafaz-lafaz tersebut tidak diletakkan secara hakiki kecuali merujuk pada makna-makna yang berciri indrawi. Jika ia mengelak bahwasanya “tangan” yang ia maksud berbeda dengan “tangan” yang mampu digambarkan akal dan dimiliki makhluk, ia telah membawa lafaz dalam bahasa Arab keluar dari makna hakiki. Dalam arti yang lain, ia yang pada awalnya berusaha keluar dari konsep takwil golongan Ahlussunah wal Jamaah terjebak dalam konsep takwil itu sendiri. Ia yang secara teori menolak majaz dalam al-Quran, ternyata malah secara praktik mengimani hal tersebut.
Ketiga, ia menganalogikan lafaz-lafaz yang menurut kita masuk dalam kategori penyerupaan Allah dengan makhluk di atas dengan sifat pengetahuan (al-‘ilmu), kehendak (al-iradah), kuasa (al-qudrah), mendengar (al-sam’) dan melihat (al-bashar) Allah, padahal keduanya jelas-jelas berbeda.
Penisbahan sifat qudrah misalnya, bagi Allah tidak mengarah pada penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Sifat tersebut bukanlah anggota badan sebagaimana lafaz-lafaz seperti (al-yad), (al-wajhu) dan (al-istiwa’). Sifat mendengar (al–sam’) dan melihat (al-bashar) tentu tidaklah serupa dengan telinga (al-udzun) dan mata (al-‘ain). Mendengar dan melihat bukanlah organ sebagaimana keduanya.
Dari sini kita dapat melihat kerancuan-kerancuan pendapat Ibnu Taimiyah dalam pemaknaan ayat-ayat mustasyabihat yang mengindikasikan penyerupaan Allah dengan makhluk. Tentu tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat kepadanya sebagai salah seorang ulama muslim.
Sikap kritis Ibnu Taimiyyah dalam menyoal tradisi-tradisi yang mapan nampaknya adalah salah satu hal yang dapat kita teladan. Kendati demikian, sifat kritis dalam memandang dan mengkaji warisan intelektual Islam tentu haruslah juga dibarengi dengan berbagai perangkat intelektual yang memadai. Hal ini agar kritik dan konsep yang ditawarkan tidak malah mengaburkan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Rasanya juga terlalu berlebihan bila mereka yang mengikuti pendapat Ibnu Taimiyyah berani menisbatkan diri dengan nama ‘manhaj salaf’, sedangkan golongan salaf berlepas diri dari apa yang mereka yakini.
Kiranya tulisan kali ini akan tepat jika diakhiri dengan perkataan Syekh Salamah al-Azzami di dalam kitabnya, Furqân al-Qur’ân bayna Shifat al-Khâliq wa Shifat al-Akwân.
“Maka apabila kalian mendengar dalam perkataan sebagian ulama salaf: sesungguhnya kami beriman bahwasanya Allah disifati dengan wajah, namun tidak seperti wajah-wajah (makhluk), disifati dengan tangan namun tidak seperti tangan (milik makhluk), maka janganlah kalian mengira bahwasanya mereka menghendaki Dzat Allah Yang Mahatinggi tersusun dari bagian-bagian. Sebagian darinya adalah tangan. Sebagian lagi adalah wajah. Yang membedakan hanyalah tangan dan wajah tersebut berbeda dengan yang disifati oleh makhluk. Sungguh terhindarlah mereka (ulama salaf) dari hal tersebut. Sungguh hal tersebut adalah penyerupaan Allah dengan makhluk.
Yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka (ulama salaf) dengan perkataan tersebut adalah lafaz “wajah” dan “tangan” telah digunakan (dalam bahasa arab) pada makna-makna dan sifat-sifat yang layak untuk dinisbatkan kepada Allah, seperti ”al-‘udzmah” (kemuliaan) dan “al-qudrah” (kuasa). Namun mereka adalah golongan yang bersikap warak, menahan diri dari menakwil sifat-sifat itu karena takut untuk melangkah ke makam yang suci (yaitu bersinggungan dengan sifat-sifat Allah).”
Oleh: Ahmad Fatih al-Faiz Binashrillah (anggota Lakpesdam NU Mesir)